Rumah adalah hak asasi manusia yang fundamental, prasyarat untuk kehidupan yang aman dan sehat. Namun di kota-kota besar, memiliki tempat tinggal menjadi semakin sulit. Apa faktor yang membuat memiliki rumah menjadi salah satu masalah dunia yang paling mendesak saat ini?
Melalui pemutaran film dokumenter Push pada 7 Desember 2020 lalu, program Layar Tancep Online membuka ruang diskusi tentang tempat tinggal, kaitannya dengan keterjangkauan. Pemutaran ini digelar oleh Gapatma, komunitas media yang memiliki fokus pada isu-isu demokrasi ekonomi dan koperasi. Berkolaborasi dengan Rujak (Center for Urban Studies), KPRN (Koperasi Perumahan Rakyat Nusantara), Perumnas, dan Yayasan Arkom Indonesia.
Pemutaran “Push”
Push adalah film dokumenter panjang dari sutradara Fredrik Gertten. Film ini mencoba menyelidiki permasalahan yang mungkin saat ini belum menjadi bahasan utama di diskusi publik kita, tapi tak mengubah kenyataan bahwa masalah ini sangatlah penting. Film ini seolah melontarkan pertanyaan menohok, “Mengapa kita tidak mampu lagi tinggal di kota kita sendiri? Lalu untuk siapa kota ini sebenarnya?”
Film Push mengisahkan perjalanan Leilani Farha, seorang pengacara Kanada, yang bekerja sebagai Direktur The Shift, sebuah gerakan global baru untuk menuntut dan mewujudkan hak asasi manusia atas perumahan. Farha mencoba menyelidiki mengapa perumahan di kota-kota di seluruh dunia menjadi sangat tidak terjangkau. Ia pun mengupas apa yang ada di balik kenaikan harga properti.
Dengan latar belakang kemampuan advokasi, Farha selama tiga tahun terakhir menjadi penyelidik PBB untuk perumahan layak. Farha terbang ke berbagai penjuru dunia untuk berbicara dengan orang-orang yang terkena dampak kenaikan harga perumahan.
Baca juga: Filming Afghanistan: Menembus Batas di Belantara Konflik
Seperti di Toronto, terjadi perbedaan ekstrem antara harga rumah dan perkembangan upah dalam tiga puluh tahun terakhir. Harga rumah telah meningkat tiga kali lipat dibanding tingkat pendapatan warganya. Bahkan di Harlem, New York, Farha bertemu dengan seorang pria yang menghabiskan 90% dari pendapatannya untuk sebuah apartemen kecil.
Lalu di London, Farha mengunjungi kawasan bekas kebakaran Menara Grenfell yang kemudian dirubuhkan untuk membuka jalan bagi perumahan mewah baru. Hal ini menyebabkan mantan penyewa tidak memiliki tempat tinggal yang terjangkau di lingkungan Notting Hill.
Sementara di Spanyol, kota Madrid menjual lebih dari 1.800 unit perumahan sosial kepada Blackstone, salah satu perusahaan investasi terkemuka, dengan harga rendah setelah krisis keuangan global. Pada tahun lalu, harga sewa di unit-unit rumah sosial tersebut meningkat hampir 50%.
Pola yang mirip muncul di sejumlah negara, mulai dari Swedia hingga Kanada. Sebuah perusahaan membeli properti tempat orang miskin tinggal, memperbaikinya, lalu menaikkan harga sewanya.
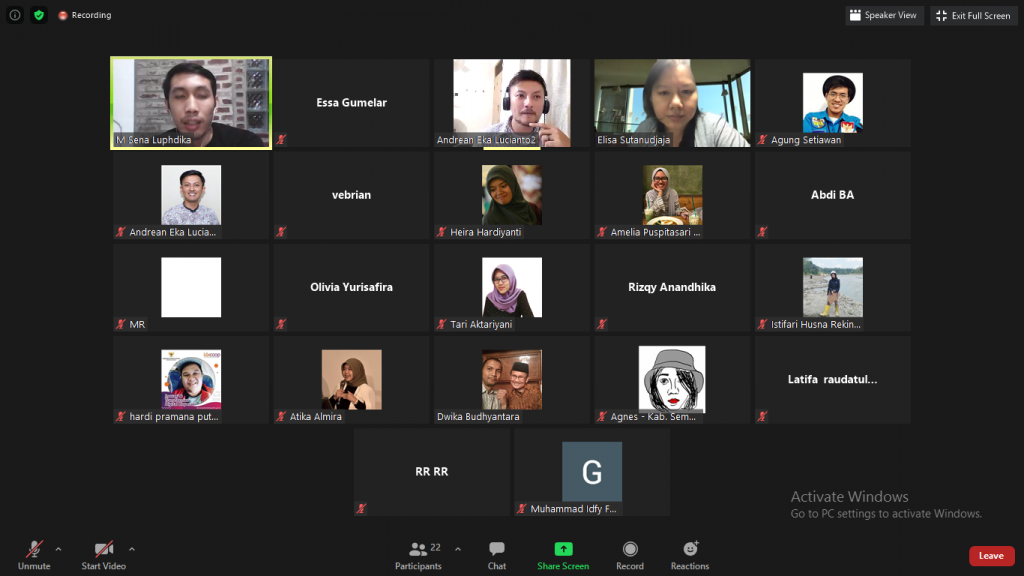
Ini hanyalah beberapa contoh dari krisis perumahan global yang dialami di hampir setiap kota di seluruh dunia, ketika harga perumahan semakin meroket namun upah pekerja tak mampu mengimbangi. Saat ini setidaknya ada 1,8 miliar orang tinggal di perumahan yang tidak layak karena harga sewa yang terlalu tinggi. Harga sewa tersebut merupakan produk dari tren keuangan global terkait investasi properti, yaitu pandangan bahwa perumahan jauh lebih berharga sebagai investasi daripada sebagai tempat tinggal.
Dalam film ini, Farha juga berbincang dengan seorang sosiolog, Saskia Sassen dan ekonom, Joseph Stiglitz. Farha telah mempelajari kesenjangan yang semakin lebar antara pendapatan rata-rata dan harga sewa. Kelas pekerja dengan ekonomi menengah ke bawah perlahan-lahan didorong semakin jauh ke luar kota, menghilangkan kesempatan mereka untuk membangun keluarga atau menjadi tua di tempat mereka tumbuh dewasa.
Fenomena Gentrifikasi
Rumah layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan permasalahan yang hingga kini belum dapat diatasi secara tuntas di Indonesia. Meskipun berbagai program telah digulirkan pemerintah untuk menyelesaikannya, kesenjangan tetap saja terus melebar. Misalnya Program Sejuta Rumah dan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), kedunya masih juga belum efektif sebagai solusi dari permasalahan perumahan di Indonesia. Fenomena gentrifikasi masih saja menjadi momok, bahkan semakin menjadi di sejumlah wilayah.
Gentrifikasi merupakan transformasi tata guna lahan yang diikuti dengan perubahan kawasan yang sebelumnya merupakan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian tergantikan oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dapat disimpulkan bahwa fenomena gentrifikasi muncul akibat adanya proses pengembangan suatu kawasan yang sukses menarik perhatian masyarakat golongan kaya, lalu menciptakan kesenjangan. Sehingga masyarakat berpenghasilan rendah menjadi rentan terusir dari kawasan huniannya. Gentrifikasi di Indonesia lebih dekat dengan istilah penggusuran lahan.
Saat ini Indonesia sedang dalam tahap mengikuti “tren perumahan.” Seperti terciptanya lingkungan baru Meikarta dan Program Seribu Tower di Jakarta. Ditegaskan oleh Elisa Sutanudjaja, Direktur Eksekutif Rujak (Center for Urban Studies), bahwa perumahan adalah hak asasi dan pemerintah bertanggung jawab atasnya. Jika dibandingkan dengan yang terjadi di Toronto, rasio perbandingan cicilan rumah terhadap rata-rata upah di Indonesia, terutama di daerah Jawa Timur, jauh lebih besar, sekitar 124% di tahun 2017.
Sejumlah Upaya
Elisa menambahkan, untuk mencegah terjadinya gentrifikasi di Indonesia, diperlukan adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat sipil yang lebih kuat. Masyarakat diimbau untuk lebih peduli pada hak atas hunian yang layak. Upaya itu bisa dimulai dengan berkoalisi membentuk sebuah asosiasi untuk perumahan. Seperti yang dipaparkan oleh Andrean Eka Lucianto (Perumnas), saat ini hanya ada bantuan individual (per keluarga) untuk perumahan MBR, sementara bantuan untuk kolektif belum ada, terkecuali untuk sebuah badan usaha dengan usia minimum 3 tahun, di sinilah letak diperlukannya dukungan pemerintah.
Baca juga: Dokumenter di Indonesia: Tetap Berkreasi meski Ekosistem Belum Jadi
Beberapa inisiatif telah dilakukan, seperti Kampung Akuarium dan Relokasi Lengkong, yang merupakan gagasan dari Rujak (Center for Urban Studies) untuk penyediaan hunian layak melalui inovasi agraria dan tata ruang. Sementara itu, Perumnas juga hadir dengan Kampung Urban, sebuah konsep perumahan sederhana yang didesain dengan standar dan sarana yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.
Meski demikian–sekali lagi–berbagai upaya itu tidak akan berhasil secara menyeluruh tanpa ada gerak dari pemerintah. Dan untuk membuat pemerintah mau bergerak, perlu adanya koalisi masyarakat sipil yang kuat untuk selalu mengingatkan, bahwa masalah ini kian mendesak. Karena kalau tidak, bukan tidak mungkin kalimat “Menjadi tuan rumah di negeri sendiri” hanya akan menjadi sekadar slogan. Bahkan yang lebih ironis, sekadar menjadi olok-olok atas kekalahan, kekalahan di negeri sendiri.

















